Izin Tambang: Bahlil Tanda Tangan, Alam Tanda Tamat
- account_circle Tajuk Maluku.com
- calendar_month Senin, 9 Jun 2025
- visibility 336
- print Cetak
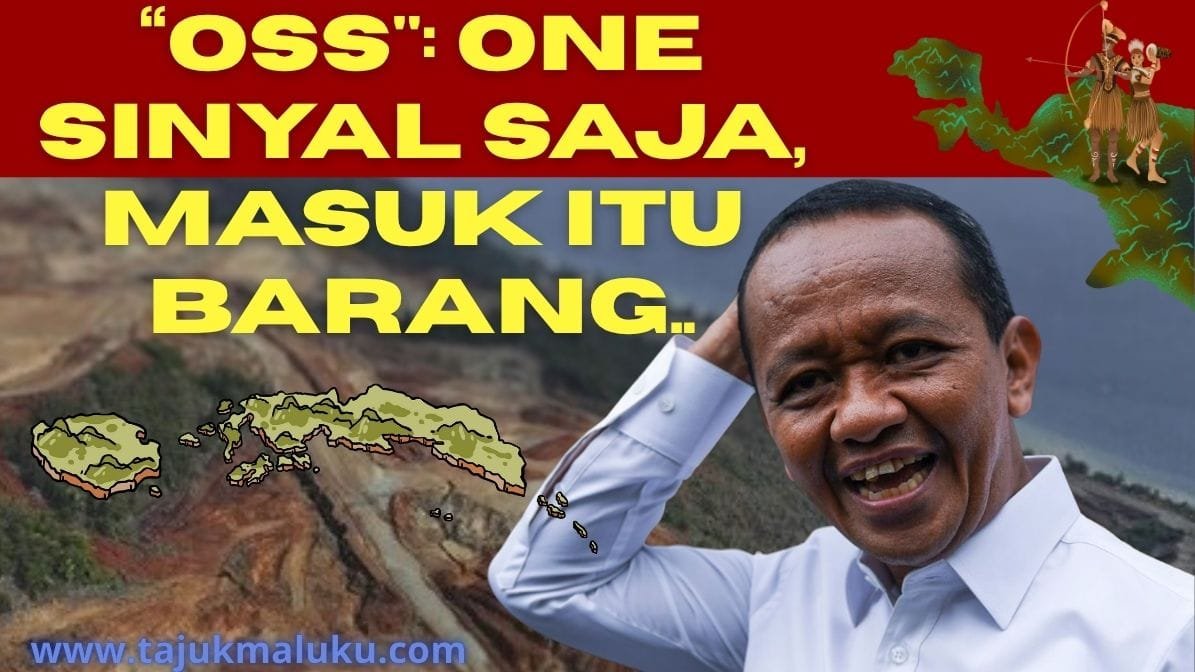
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Tajukmaluku.com-Narasi legalitas perizinan tambang seringkali tampil sebagai tameng moral, seolah proses panjang birokrasi dan setumpuk dokumen adalah jaminan mutlak bahwa tambang beroperasi secara etis dan bertanggung jawab. Sayangnya, realitas di lapangan lebih mirip dagelan: di balik setiap tanda tangan dan izin, ada kemungkinan transaksi dan kompromi. Satu budaya yang meneguhkan klientalisme bisnis dan koncoisme-kompromi kuasa.
Tulisan panjang soal “labirin perizinan” tambang yang terlihat teknokratik itu, sesungguhnya adalah narasi untuk menyamarkan kegagalan pengelolaan birokrasi yang terbuka, akuntable dan pro terhadap social konteks. Tanggung jawab menjadi urusan kolektifitas. Pada titik ini, publik mulai menguji narasi besar teknokrasi yang ditulis seperti pengumuman perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di pemerintahan kabupaten: Pertanyaan apakah semua ‘pintu’ birokrasi itu benar-benar berfungsi sebagai sekat kontrol? Harus dijawab dengan fakta, bukan ilusi apalagi menggunakan diksi mestinya, seharusnya dll. Alibi bagi pembela ‘piring’ agar tak pecah.
Kita tidak sedang membicarakan kekeliruan prosedur administratif. Yang sedang terjadi di banyak wilayah—dari Wawonii, Mandiodo, Halmahera, hingga Pulau Gag di Raja Ampat—adalah soal perampasan ruang hidup dengan restu negara. Dokumen AMDAL, IPPKH, hingga IUP bisa jadi sah secara administratif, tapi itu tak otomatis sah secara moral, sosial, atau ekologis.
Pertanyaannya bukan ‘apakah izinnya lengkap’, tapi ‘kenapa izin bisa keluar di kawasan hutan lindung, di pulau kecil, di wilayah adat, atau di wilayah rawan ekologis’? Jawabannya sederhana tapi menyakitkan: karena politik izin di Indonesia telah direduksi jadi transaksi, bukan pertimbangan keberlanjutan.
Bahlil dan Politik Izin: Kuasa Di Balik Meja
Bahlil bukan hanya pejabat teknokrat. Ia politisi, mantan Ketua Umum HIPMI, dan tokoh kunci dalam pemetaan ulang izin tambang pasca UU Cipta Kerja. Lewat kewenangan Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA), Bahlil dan lembaganya memegang kuasa besar: bisa mencabut atau menerbitkan izin usaha atas nama “penyederhanaan birokrasi”.
Namun yang terjadi bukan penyederhanaan, melainkan pemusatan kuasa. Pada 2022, Bahlil mengumumkan pencabutan 2.078 Izin Usaha Pertambangan (IUP) karena dianggap tidak produktif. Tapi dalam praktiknya, sebagaimana temuan ICW dan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), banyak pencabutan itu justru membuka ruang bagi “kelompok baru” yang lebih dekat ke lingkar kekuasaan. Izin yang dicabut bukan diakhiri, melainkan dialihkan.
KPK dalam kajiannya tentang tata kelola minerba 2020-2022 menemukan banyak celah dalam sistem perizinan yang dikelola Kementerian Investasi, termasuk tidak sinkronnya data OSS dengan kementerian teknis dan lemahnya verifikasi lapangan.
Dalam laporan WALHI 2023, tercatat bahwa perluasan tambang nikel di Indonesia bagian timur terjadi seiring ekspansi korporasi baru yang memiliki koneksi langsung dengan elite partai politik. Di sinilah posisi Bahlil semakin problematik. Bahlil, alih-alih memperbaiki fondasi, justru mempercepat ekspansi. Mengabil resiko merusak tanah adat, membabat kebudayaan, dan mengilangkan jejak Sejarah. Bahlil tak pantas di bela. Urusan Bahlil bukan hanya soal mengenyangkan negara, tetapi harus bisa menutup luka sejarah dan menghapus air mata rakyat diatas derita pertambangan.
Di bawah tangan Bahlil, investasi tambang tak hanya soal pembangunan, tapi instrumen politik. Peran Bahlil dalam tim pemenangan pemilu membuat setiap izin tambang berpotensi menjadi konsesi kekuasaan. Dalam konteks itu, perizinan bukan alat pembangunan berkelanjutan, melainkan bagian dari patronase politik.
WALHI mencatat, sejak 2021 terjadi lonjakan tajam izin tambang di kawasan rawan bencana dan wilayah adat. Ini tidak lepas dari skema OSS yang terpusat dan minim partisipasi publik. Bahkan, ketika konflik di Pulau Wawonii dan Pulau Gag mencuat, Bahlil justru membela korporasi, menyebut warga yang menolak tambang sebagai penghambat pembangunan.
Narasi legalitas kolektif yang digunakan untuk membela Bahlil hanyalah tameng. Fakta bahwa Menteri Investasi memiliki otoritas administratif, tetapi juga kekuasaan politik membuatnya tak bisa sekadar bersembunyi di balik regulasi. Legalitas yang dibentuk dalam ruang gelap kekuasaan bukanlah legitimasi.
Artinya, setiap kebijakan Bahlil terkait izin tambang bukan sekadar keputusan administratif, tapi bagian dari strategi konsesi politik. Tambang menjadi imbalan atau alat untuk mempertahankan pengaruh kekuasaan. Maka tidak heran, pulau-pulau kecil yang dulunya hutan lindung kini berubah menjadi konsesi nikel—salah satunya adalah Pulau Gag.
ICW menegaskan, dalam sistem hukum yang rentan suap dan oligarki politik, dokumen legal bisa diproduksi untuk menutupi ketidakadilan. Jika Menteri Investasi itu ikut menentukan siapa yang layak mendapat izin berdasarkan kedekatan, maka legalitas itu menjadi transaksi.
Sistem Bisa Ditembus Dari Banyak Sisi
Birokrasi multilapis yang katanya jadi “checks and balances” justru membuka lebih banyak pintu kompromi. Dalam laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) tahun 2023, sektor pertambangan masih berada di peringkat 3 tertinggi sektor paling rawan korupsi, setelah infrastruktur dan kehutanan.
KPK pada 2014 mencatat 1,3 juta hektar tambang berada di kawasan konservasi dan 4,9 juta hektar di kawasan lindung—semua legal tapi merampas uang negara sekitar Rp 15,9 triliun per tahun karena tiadanya PNBP. Belum diolah data terbaru, namun realitas WKM di Maluku Utara (7,3 ha bukaan hutan tanpa IPPKH) membuktikan hutan takluk bukan akibat izin non-izin—tapi rencana.
Data KLHK juga menunjukkan, hingga September 2023, sebanyak 40 % dari total 854.684 ha aktivitas pertambangan berada di kawasan hutan, dengan hampir setengahnya tanpa IPPKH.
Jadi meski ada “pintu IPPKH”, pengawasan tidak merata, regulasi bisa “diterabas”.
Salah satu contohnya adalah temuan KPK dalam kajian tahun 2020 soal tambang ilegal di kawasan hutan:
“Sebanyak 2.741 IUP berada di kawasan hutan tanpa IPPKH. Artinya, ribuan perusahaan tambang secara terang-terangan beroperasi secara ilegal, tapi tetap bisa mengekspor hasil tambangnya.
”Jadi di mana fungsi “pintu pengawasan” itu tadi? Jika semua pintu bisa dilalui dengan uang atau koneksi politik, maka itu bukan labirin—itu pasar gelap yang dipoles dengan tinta basah birokrasi.
Dokumen AMDAL bisa dibuat dari balik meja, tanpa pernah benar-benar berkonsultasi dengan masyarakat terdampak. “Partisipasi publik” seringkali hanya formalitas: dilakukan di desa yang tidak terkena dampak langsung, atau dengan undangan terbatas, bahkan dibungkam. Contoh konkret adalah Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara, di mana masyarakat menolak keras tambang nikel karena mengancam sumber air dan lahan pertanian. Namun pemerintah daerah dan pusat tetap ngotot memberi izin.
Apa gunanya sertifikat kelayakan lingkungan jika ia tidak melindungi masyarakat dan ruang hidup mereka? Jawabannya: karena sertifikat itu bukan alat perlindungan, tapi tameng legalitas untuk menyingkirkan penolakan.
Jika Semua Pihak Terlibat, Mengapa Tak Ada yang Bertanggung Jawab?
Narasi “tanggung jawab kolektif” itu bagus di atas kertas, tapi justru membuat semua orang bisa cuci tangan. Ketika konflik sosial pecah, lingkungan rusak, atau tambang meninggalkan lubang maut, tak satu pun instansi benar-benar turun tangan menindak.
Laporan WALHI 2024 mencatat: 96% konflik agraria di sektor tambang tidak selesai secara adil. 86% pengaduan lingkungan akibat tambang tidak ditindaklanjuti secara serius oleh KLHK atau ESDM.
Salah satu ironi besar dalam perizinan tambang adalah penghapusan kewenangan daerah sejak UU Minerba disahkan (UU No. 3/2020). Kini, semua IUP diterbitkan oleh pemerintah pusat. Jadi ketika ada kerusakan, masyarakat lokal dilarang mengatur, tapi diwajibkan menanggung dampaknya.
Ketimpangan kuasa ini memperlihatkan bahwa perizinan bukan soal prosedur teknis, tapi bagian dari tata kelola politik sumber daya yang sentralistik, elitis, dan minim akuntabilitas.
Jangan biarkan labirin birokrasi jadi dalih untuk menutupi jejak kejahatan ekologis. Ini bukan soal “pintu” yang banyak, tapi soal semua pintu dijaga oleh tangan yang sama: politik rente dan keserakahan modal.
Karena jika semuanya sesuai prosedur, lalu tetap menindas rakyat dan merusak alam, maka kesimpulannya hanya satu: yang perlu ditambang bukan lagi tanah, tapi nurani para pengambil kebijakan.*
Fadel Rumakat, Aktivis dan Pegiat Sosial di Maluku. Pendiri Rumah Muda Anti Korupsi (RUMMI) ini kerap terjun dalam advokasi problem lingkungan dan korupsi di Maluku.
- Penulis: Tajuk Maluku.com



























Saat ini belum ada komentar